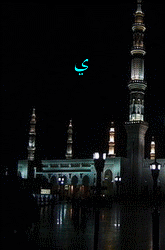Oleh: Abduh Zulfidar Akaha
Suntingan & Editor: Makmur Effendi
Callighraphy@by: Makmur Effendi
Selain berbagai ajaran dan pemahaman sesat di atas, yang membuat mereka hanya mau beriman kepada Al-Qur`an dan menerima Al-Qur`an saja sebagai satu-satunya kitab sumber syariat; mereka pun juga mempunyai sejumlah alasan kenapa menolak Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.
Meskipun menurut pengakuan mereka, sebetulnya yang mereka tolak bukanlah Sunnah Rasul, karena Sunnah Rasul adalah Al-Qur`an itu sendiri. Akan tetapi, yang mereka tolak sejatinya adalah hadits-hadits yang dinisbatkan kepada Nabi. Sebab, hadits-hadits tersebut –menurut mereka– merupakan perkataan-perkataan yang dikarang oleh orang-orang setelah Nabi. Dengan kata lain; hadits-hadits itu adalah buatan manusia!
Setidaknya, ada sembilan alasan kenapa mereka menolak hadits Nabi, yaitu:
I. Yang Dijamin Allah Hanya Al-Qur`an, Bukan Sunnah
Sekiranya Allah menghendaki akan menjaga agama Islam ini dengan Al-Qur`an dan Sunnah, niscaya Dia akan memberikan jaminan tersebut dalam Kitab-Nya. Akan tetapi, karena Allah menghendaki bahwa hanya Al-Qur`anlah yang Dia jamin, maka Allah sama sekali tidak memberikan jaminan kepada selain Al-Qur`an. Allah tidak memberikan jaminan-Nya kepada Sunnah. Allah telah mencukupkan agama ini dengan Al-Qur`an saja tanpa yang lain.
Allah Jalla wa ‘Ala berfirman,
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ .
“Sesungguhnya Kamilah yang telah menurunkan adz-dzikr (Al-Qur`an), dan Kami benar-benar akan menjaganya.” (Al-Hijr: 9)
Dalam ayat ini, yang dijamin akan dijaga oleh Allah adalah Al-Qur`an.
Bantahan
Orang Inkar Sunnah menafsirkan ayat ini dengan hawa nafsunya.
Kalau saja mereka mau berpikir jernih dan melihat dengan cermat, tentu mereka tidak akan berkata demikian. Sebab, kata yang dipakai di sana adalah “adz-dzikr,” bukan Al-Qur`an. Sekiranya yang dimaksud Allah adalah hanya menjaga Al-Qur`an saja, niscaya Dia akan mengatakannya secara tegas, dengan menyebutkan kata “Al-Qur`an,” bukan “adz-dzikr.” Sebagaimana termaktub dalam banyak ayat Al-Qur`an yang menyebutkan demikian.
Misalnya;
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ .
“Dan apabila dibacakan Al-Qur`an, maka dengarkan dan perhatikanlah baik-baik agar kalian mendapat rahmat.” (Al-A’raf: 204)
Akan tetapi, yang dipakai di sini adalah kata “adz-dzikr.” Dan, lafazh adz-dzikr sebagai ganti Al-Qur`an ini mempunyai makna dan hikmah tersendiri. Karena ia bisa bermakna sebagai Al-Qur`an dan Sunnah sekaligus. Sebab, selain Allah menjamin Al-Qur`an dengan penjagaan langsung dari sisi-Nya, Allah pun menjaga Sunnah Nabi-Nya melalui para sahabat dan ulama penerus mereka. Bagaimanapun juga, penjagaan Allah terhadap agama ini mencakup penjagaan-Nya terhadap Sunnah, karena Sunnah-lah yang menjelaskan Al-Qur`an.
Bagaimana bisa dikatakan bahwa Allah menjaga sesuatu yang dijelaskan (Al-Qur`an), dan meninggalkan sesuatu yang menjelaskan (Sunnah)? Sementara kita –umat Islam– tidak mungkin bisa memahami Al-Qur`an dan mengamalkan ajaran-Nya tanpa bantuan Sunnah Al-Muthahharah.
Itulah makanya, Allah Ta’ala berfirman,
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .
“Maka, bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr jika kalian tidak mengetahui.” (An-Nahl :43)
Sebagian ahli tafsir mengatakan,[1] bahwa yang dimaksud dengan ahlu dzikr adalah ahlul ilmi, yakni para ulama. Sedangkan sebagian lagi mengatakan, bahwa ahlu dzikr adalah ahlul Qur`an, yang tidak lain adalah ulama juga. Dan, tidak disebut sebagai ulama jika tidak menguasai Al-Qur`an dan Sunnah sekaligus.
II. Nabi Sendiri Melarang Penulisan Hadits
Sama seperti Syiah yang tidak konsisten dengan sikapnya terhadap Umar bin Al-Khathab Radhiyallahu Anhu. Betapa bencinya mereka (orang-orang Syiah) kepada Umar yang dianggap sebagai perampas hak kekhalifahan Ali bin Abi Thalib Karramallahu Wajhah.
Mereka juga mengatakan, bahwa Umar-lah yang mengharamkan nikah mut’ah, bukan Nabi. Namun, di satu sisi, mereka memuji-muji Umar atas sikapnya yang menegur bahkan sampai memukul Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dikarenakan banyaknya Abu Hurairah meriwayatkan hadits dari Nabi.
Begitu pula dengan kelompok inkar Sunnah. Di satu sisi mereka menolak hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. Tetapi di sisi lain, manakala ada hadits yang sesuai dengan nafsu syahwat mereka, maka mereka pun mendukungnya. Bahkan, tanpa malu-malu mereka menjadikannya senjata untuk membenarkan sikap mereka dalam menyerang Sunnah Nabi.
Mereka selalu mendengung-dengungkan dan berpegang pada hadits Nabi yang mengatakan,
لَا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ فَمَنْ كَتَبَ عَنِّي شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ . (رواه أحمد ومسلم والدارمي عن أبي سعيد الخدري)
“Janganlah kalian menulis sesuatu pun dariku selain Al-Qur`an. Barangsiapa yang menulis sesuatu dariku selain Al-Qur`an, maka hendaklah dia menghapusnya.” (HR. Ahmad, Muslim, dan Ad-Darimi dari Abu Said Al-Khudri)[2]
Yang dimaksud “tentang aku” atau “dariku” dalam hadits ini adalah segala yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, baik itu berupa perkataan (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah fi’liyah), maupun persetujuan (sunnah taqririyah).[3]
Dan hadits lain yang diriwayatkan Imam Al-Khathib Al-Baghdadi (w. 463 H) dari Abu Hurairah, yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menemui sebagian sahabat yang ketika itu sedang menulis hadits.
Beliau berkata,
“Kalian sedang menulis apa?”
Mereka menjawab,
“Hadits-hadits yang kami dengar dari Anda.”
Beliau bersabda,
“Apakah kalian berani menulis kitab selain Kitab Allah? Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian itu menjadi sesat dikarenakan mereka menulis kitab bersama-sama Kitab Allah Ta’ala.”[4]
Dua hadits ini dan hadits-hadits lain yang senada, mereka jadikan alasan untuk menolak Sunnah. Sebab, Nabi sendiri telah melarang penulisan hadits. Lalu, bagaimana mungkin umatnya mengaku memiliki hadits-hadits yang bersumber dari Nabi? Jadi, sesungguhnya yang namanya hadits Nabi itu tidak ada, karena Nabi sendirilah yang melarang menulis hadits. Dan, memang tidak mungkin bagi Nabi untuk mengatakan perkataan-perkataan selain Al-Qur`an!
Bantahan
Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi (w. 676 H) berkata,
“Hadits-hadits tentang larangan menulis hadits telah mansukh (dihapus) dengan hadits-hadits yang membolehkan penulisan hadits. Sebab, ketika itu Nabi melarang menulis hadits karena khawatir hadits-hadits tersebut akan tercampur dengan Al-Qur`an. Kemudian, ketika kekhawatiran itu hilang dikarenakan para sahabat sudah matang Al-Qur`annya, maka Nabi pun mengizinkan para sahabat untuk menulis hadits.”[5]
Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dilarang adalah menulis hadits dalam satu tempat yang sama dengan Al-Qur`an. Sebab, dikhawatirkan seseorang akan bingung ketika membacanya, mana yang Al-Qur`an dan mana yang hadits Nabi? [6]
Dalam hal ini, banyak hadits yang menyebutkan dibolehkannya menulis hadits. Di antaranya, yaitu:
1. Hadits yang menceritakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersama kaum muslimin menaklukkan kota Makkah, lalu beliau berdiri menyampaikan khutbah. Ketika itu ada seorang laki-laki dari Yaman yang bernama Abu Syah meminta kepada Nabi agar khutbah tersebut dituliskan untuknya.
Nabi pun bersabda,
اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ . ) متفق عليه عن أبي هريرة(
“Tuliskanlah untuk Abu Syah.” (Muttafaq Alaih dari Abu Hurairah)[7]
2. Abdullah bin Amru bin Al-Ash Radhiyallahu Anhuma berkata,
“Dulu saya selalu menulis setiap perkataan yang saya dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam karena ingin menjaganya. Tetapi orang Quraisy melarang saya. Mereka mengatakan bahwa Rasul juga manusia biasa yang bisa marah dan gembira. Lalu, saya pun sementara menahan diri untuk tidak menulis hadits, hingga saya sampaikan hal ini kepada Rasulullah.
Maka, beliau pun memberikan isyarat dengan jari telunjuknya ke arah mulutnya seraya bersabda,
اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ . (رواه أبو داود)
“Tulislah! Demi Yang jiwaku berada di Tangan-Nya, tidak ada yang keluar darinya kecuali kebenaran.” (HR. Abu Dawud)[8]
Setelah menyebutkan sejumlah hadits tentang adanya kegiatan penulisan hadits masa Nabi, atas perintah beliau dan atau sepengetahuan beliau, DR. Salim Ali Al-Bahnasawi berkata, “Ini semua menunjukkan bahwa dilarangnya penulisan hadits ketika itu tidak lain adalah karena kekhawatiran tercampurnya Sunnah dengan Al-Qur`an. Untuk itu, apabila penyebab ini telah hilang, maka penulisan hadits adalah suatu keharusan.”[9]
Para ulama menggabungkan antara hadits-hadits yang melarang dan membolehkan penulisan hadits, sebagai berikut:
- Hadits-hadits yang membolehkan (menyuruh) menulis hadits telah menghapus hadits-hadits yang melarang. Dan, hal ini terjadi pada masa awal-awal Islam ketika masih dikhawatirkan terjadi kerancuan atau campur aduk antara Al-Qur`an dan hadits.
- Larangan menulis hadits adalah bagi orang yang hafalannya kuat, agar dia tidak tergantung pada tulisan. Adapun orang yang hafalannya lemah, maka dia boleh menulisnya.
- Larangan menulis hadits khusus bagi yang menuliskannya dalam satu tempat yang sama dengan tulisan Al-Qur`an, sebab dikhawatirkan akan bercampur.
- Nabi hanya melarang menulis hadits pada saat turunnya wahyu dan ditulisya ayat yang baru saja turun.
- Larangan menulis hadits hanya bagi yang belum pandai menulis, karena dikhawatirkan salah. Adapun yang sudah mahir menulis, maka dia boleh menulis hadits.
- Larangan hanya berlaku bagi para penulis wahyu yang bertugas menulis setiap wahyu yang turun. Adapun selain mereka, maka diperbolehkan menulis hadits.
Dan, dibolehkannya menulis hadits ini adalah masalah yang sudah disepakati oleh para ulama. Sebagaimana dinukil oleh Al-Khathib Al-Baghdadi, Al-Hafizh Ibnu Shalah, dan lain-lain.[10] Lagi pula, Nabi pun pernah (menyuruh sahabat untuk) menulis surat kepada para pemimpin kabilah di sekitar Madinah dan jazirah Arab, Kaisar, Heraklius, perjanjian damai Hudaibiyah, dan lain-lain.
III. Hadits Baru Dibukukan Pada Abad Kedua Hijriyah
Orang-orang inkar Sunnah sama saja dengan para orientalis dalam hal ini. Mereka mengatakan bahwa hadits-hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang terdapat dalam kitab-kitab Sunnah banyak bohongnya dan mengada-ada karena baru dibukukan ratusan tahun setelah Nabi wafat. Kata mereka, isi kitab-kitab yang diklaim sebagai berasal dari Nabi itu tak lain merupakan hasil dari gejolak politik, sosial, dan keagamaan yang dialami kaum muslimin pada abad pertama dan kedua. Jadi, bagaimana mungkin kitab yang dibukukan sekitar dua abad setelah wafatnya Nabi diyakini sebagai Sunnah Nabi?[11]
Ignaz Goldziher (1850 – 1921 M), salah seorang tokoh orientalis Yahudi dari Hongaria mengatakan, “Sebagian besar hadits adalah hasil perkembangan keagamaan, politik, dan sosial umat Islam pada abad pertama dan kedua. Tidak benar jika dikatakan bahwa hadits itu merupakan dokumen umat Islam sejak masa pertumbuhannya. Sebab, itu semua merupakan buah dari usaha umat Islam pada masa kematangannya.”[12]
Kata orang inkar Sunnah, apabila memang benar bahwa hadits-hadits itu bersumber dari Nabi, semestinya sudah dibukukan sejak masa Nabi hidup. Bukan dua abad setelah beliau wafat.
Bantahan
Pertama kali yang ingin kami katakan di sini adalah, bahwa sebetulnya anggapan seperti ini sama saja dengan menunjukkan kebodohan mereka sendiri. Sebab, yang mereka jadikan patokan adalah kitab Shahih Al-Bukhari (194 H – 256 H), Shahih Muslim (204 H – 262 H), dan kitab-kitab hadits seterusnya yang memang ditulis pada dan setelah abad kedua Hijriyah.
Entah karena tidak tahu atau pura-pura tidak tahu mereka ini, bahwa sesungguhnya pembukuan hadits-hadits Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sudah dimulai jauh sebelum itu.
Tentu, ada perbedaan antara penulisan dan pembukuan.
Orang menulis, meskipun banyak yang ditulis, belum tentu menjadi buku jika tidak dibukukan.
Adapun pembukuan, adalah pengumpulan dari tulisan-tulisan yang telah disusun secara rapi. Apa pun definisinya, yang pasti para sahabat telah menulis hadits-hadits Nabi sejak beliau masih hidup. Akan tetapi dikarenakan sejumlah faktor, tulisan-tulisan hadits yang tersebut belum dikumpulkan di satu tempat dalam satu buku.
Kami tidak hendak menyebutkan berbagai alasan kenapa hadits-hadits tersebut tidak segera dibukukan, karena orang Inkar Sunnah yang sudah dibutakan mata dan hatinya oleh Allah tidak akan mau tahu.
Namun, kami hanya akan memberikan sejumlah fakta bahwa pembukuan hadits sudah dimulai sebelum abad kedua, dan bahwa kitab Shahih Al-Bukhari bukanlah kitab hadits yang pertama kali dalam Islam.
- Khalifah Umar bin Abdil Aziz (w. 99 H) yang termasuk generasi tabi’in, yakni generasi yang langsung bertemu para sahabat, dan mengambil ilmu langsung dari mereka, telah memerintahkan semua gubernurnya di seluruh wilayah Islam untuk mengumpulkan hadits-hadits Nabi. Umar berkata, “Carilah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan kumpulkanlah.”[13]
Para ulama mengatakan, “Adapun pembukuan hadits, maka itu terjadi pada penghujung abad pertama pada masa Khalifah Umar bin Abdil Aziz, atas perintahnya.”[14]
- Abu Bakar Muhammad bin Amru bin Hazm[15] (w. 98 H) atas perintah Khalifah Umar bin Abdil Aziz, membukukan hadits-hadits Nabi yang ada pada Amrah binti Abdirrahman dan Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar.
- Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri (58 H – 124 H), salah seorang ulama tabi’in, menyambut baik perintah Umar bin Abdil Aziz untuk membukukan hadits. Dia pun mengumpulkan hadits-hadits Nabi yang sudah dia tulis dan hafal, lalu dia letakkan dalam satu buku. Bisa dikatakan, jerih payah Ibnu Syihab ini adalah awal dari aktivitas penyusunan dan pembukuan hadits. Para ulama mengatakan, “Kalau bukan karena Az-Zuhri, sungguh akan banyak Sunnah yang hilang.”[16]
- Selanjutnya di Makkah, Ibnu Juraij (w. 150 H) juga membukukan hadits.
- Masih di Makkah, Ibnu Ishaq (w. 151 H) pun membukukan hadits.
- Di Madinah; Said bin Abi Arubah (w. 156 H), Ar-Rabi’ bin Shabih (w. 160 H), dan Imam Malik bin Anas (w. 179 H).
- Di Syam; Abu Umar Al-Auza’i (w. 157 H), Husyaim bin Basyir (w. 173 H).
- Di Bashrah; Hammad bin Salamah (w. 167 H).
- Di Kufah; Sufyan Ats-Tsauri (w. 161 H).
- Di Yaman; Ma’mar bin Rasyid (w. 154 H).
- Di Mesir; Al-Laits bin Sa’ad (w. 154 H).
- Di Khurasan; Abdullah bin Al-Mubarak (w. 181 H).
Kemudian, memasuki abad II yang sebetulnya adalah kelanjutan dari masa sebelumnya, pembukuan hadits mulai lebih teratur penyusunannya dari segi pembagian bab, masalah yang dibahas, hadits yang berulang, dan sahabat yang meriwayatkan. Lalu, muncullah kitab-kitab hadits berikutnya;
- Musnad Abu Dawud Sulaiman Ath-Thayalisi (w. 204 H).
- Musnad Abu Bakar Abdullah Al-Humaidi (w. 219 H).
- Musnad Imam Ahmad bin Hambal (w. 241 H).
- Musnad Abu Bakar Ahmad bin Amru Al-Bazzar (w. 292 H)
- Musnad Abu Ya’la Ahmad Al-Maushili (w. 307 H).
- Al-Jami’ Ash-Shahih/Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari (w. 256 H).
- Al-Jami’ Ash-Shahih/Imam Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi (w. 261 H).
- Sunan At-Tirmidzi/Imam Abu Isa At-Tirmidzi (w. 279).
- Sunan Abu Dawud/Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sijistani (w. 275 H).
- Sunan An-Nasa`i/Abu Abdirrahman An-Nasa`i (w. 303 H).
- Sunan Ibnu Majah/Muhammad bin Yazid bin Majah (w. 275 H).
- Sunan Asy-Syafi’i/Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i (w. 204 H).
- Sunan Ad-Darimi/Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi (w. 255 H).
- Sunan Ad-Daruquthni/Ali bin Umar Ad-Daruquthni (w. 385 H).
- Dan lain-lain…
Kalau orang inkar Sunnah mau jujur, dari mana mereka tahu bahwa Imam Al-Bukhari hidup pada abad kedua dan bahwa pada masa Nabi belum ada pembukuan[17] hadits? Bukankah itu dari sejarah? Bukankah jika mereka mengetahui hal ini, artinya mereka juga membaca buku? Dan, bukankah mereka juga sama saja dengan mengambil pendapat orang lain dalam masalah ini? Tetapi, kenapa mereka selalu mengatakan; ikuti saja Al-Qur`an, jangan ikuti yang lain?!!
Ringkas kata, apa yang mereka katakan bahwa Sunnah baru dibukukan pada abad kedua adalah tidak benar.
Sebab, sebelum abad kedua pun, sudah banyak ulama umat ini yang membukukan Sunnah. Selanjutnya, jika dengan tuduhan ini mereka ingin mengatakan bahwa karena dibukukan ratusan tahun setelah Nabi meninggal, maka isi kitab-kitab Sunnah itu adalah bohong dan tidak bisa dianggap sebagai Sunnah Nabi; juga tidak benar. Sebab, justru isi dari kitab-kitab Sunnah itulah yang sudah diketahui, dihafal, dan diamalkan sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Bagaimanapun juga, tidak selalu suatu masalah atau peristiwa harus dibukukan saat itu juga. Betapa banyak buku-buku tentang suatu kasus atau peristiwa tertentu/bersejarah yang baru dibukukan setelah semua pelakunya meninggal. Dan betapa banyak biografi atau perkataan-perkataan seseorang yang baru dibukukan bertahun-tahun setelah yang bersangkutan tiada.
[1] Lihat misalnya; Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur`an/Imam Abu Abdillah Al-Qurthubi/jilid 5/hlm 2872/terbitan Dar Al-Fikr, Beirut/Cetakan I/1999 M – 1419 H, dan Taysir Al-Karim Ar-Rahman/Syaikh Abdurrahman As-Sa’di/hlm 441/terbitan Markaz Fajr li Ath-Thiba’ah, Kairo/Cetakan I/2000 M – 1421 H.
[2] Hadits shahih. Lihat; Shahih Muslim/Kitab Az-Zuhd wa Ar-Raqa`iq/Bab At-Tatsabbut fi Al-Hadits wa Hukm Kitabati Al-’Ilm/hadits nomor 5326, Musnad Ahmad/Kitab Baqi Musnad Al-Muktsirin/Bab Musnad Abi Sa’id Al-Khudri/hadits nomor 1110, dan Sunan Ad-Darimi/Kitab Al-Muqaddimah/Bab Man Lam Yara Kitabata Al-Hadits/451. Semuanya dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu.
[3] Sebagian ulama ada juga yang menambahkan macam sunnah yang keempat, yaitu sunnah pembawaan (sunnah washfiyah).
[4] Mabahits fi ‘Ulum Al-Hadits/Syaikh Manna’ Al-Qatha/Maktabah Wahbah – Kairo/hlm 29-31/Cetakan IV/2004 M – 1425 H, menukil dari Al-Baghdadi dalam Taqyid Al-’Ilm, yang dikoreksi DR. Yusuf Al-Isy.
[5] Syarh Shahih Muslim/Imam Abu Zakariya An-Nawawi/juz 18/hlm 104/terbitan Maktabah At-Taufiqiyah, Kairo.
[6] Sda.
[7] Lihat; Shahih Al-Bukhari/Kitab Ad-Diyyat/Bab Man Qutila Lahu Qatil/hadits nomor 6372, dan Shahih Muslim/Kitab Al-Hajj/Bab Tahrim Makkah wa Shaidiha/hadits nomor 2414. Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan Abu Dawud juga meriwayatkan hadits ini.
[8] Sunan Abi Dawud/Kitab Al-’Ilm/Bab fi Kitab Al-’Ilm/hadits nomor 3161. Imam Ahmad (6221) dan Ad-Darimi (484) juga meriwayatkan hadits ini.
[9] As-Sunnah Al-Muftara ‘Alaiha/DR. Salim Ali Al-Bahnasawi/hlm 53/Dar Al-Wafa` – Manshurah, Mesir/Cetakan ke-IV/1992 M- 1413 H.
[11] Kelompok inkar Sunnah bisa saja membantah bahwa mereka berpendapat demikian bukan karena terpengaruh kaum orientalis. Karena mereka memang sangat anti mengutip pendapat orang lain dalam menyebarkan dakwah sesatnya. Mereka selalu mengatakan, “Ikuti saja Al-Qur`an, itu sudah cukup. Jangan ikuti siapa pun selain Al-Qur`an.” Hal ini bisa dilihat dari sikap tokoh-tokoh mereka, seperti Taufiq Shidqi, Ahmad Amin, dan Abu Rayyah yang tidak mau menisbatkan pendapatnya kepada para pendahulunya atau kepada orientalis yang pendapatnya mereka kutip. (Lihat; http://www.islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?lang=A&id=36524)
[12] Dikutip dari buku Difa’ ‘An Al-Hadits An-Nabawi/DR. Ahmad Umar Hasyim/hlm 36.
[13] As-Sunnah Al-Muftara ‘Alaiha/DR. Salim Ali Al-Bahnasawi/hlm 66.
[14] Mabahits fi ‘Ulum Al-Hadits/Syaikh Manna’ Al-Qaththan/hlm 35.
[15] Ada yang mengatakan, bahwa gubernur Madinah waktu itu adalah Amru bin Hazm,ayahnya Muhammad bin Amru ini. Wallahu a’lam.
[16] Op. cit. no. 39.
[17] Pembukuan, bukan penulisan.
Filed under: Argumentasi Golongan Ingkar Sunnah | Tagged: Abu Hurairah, Al-A'raf, Allah, Argumentasi Golongan Ingkar Sunnah, Islam, Kitab, Muhammad, Qur'an, Religion and Spirituality, Sunnah | 2 Comments »